Pertama kali saya mengetahui tentang adanya sebuah novel yang berjudul Landorundun melalui facebook; melalui diskusi-diskusi di salah satu grup facebook komunitas Toraja. Saat itu, gairah saya untuk membaca novel tersebut langsung membara. Mengapa? Setahu saya inilah novel 'modern' pertama dari Toraja!!! Saya langsung ke Gramedia (Yogyakarta), mencari di katalog, dan benar, ada judul novel Landorundun. Tetapi sayangnya stock-nya kosong.... Melalui facebook saya mengetahui siapa penulisnya: Rampa Maega, sebuah nama yang sangat unik, bahkan sempat chatting dengan beliau. Saya menemukan novel tersebut secara tidak langsung justru ketika pulang ke Toraja pada pertengahan 2012, dalam sebuah acara di sebuah hotel; bahkan bertemu langsung dengan sang penulis yang ternyata masih muda. Tanpa banyak basa-basi, walau dengan kantong tipis, saya langsung membeli novel tersebut dan meminta tanda tangan penulis.
Dalam hal ini, kebanggaan, terharu, dan kegembiraan yang luar biasa dalam diri saya telah mendahului isi novel tersebut: saya gembira luar biasa jauh sebelum saya membaca novel tersebut. Sebagai orang yang sedang jatuh cinta pada sastra, khususnya pada novel, lahirnya sebuah novel dari Toraja seperti hujan di siang bolong alias sama sekali tidak saya duga. Selama ini, dunia sastra di Toraja hampir sama dengan apa yang tersebar tak beraturan di Toraja dewasa ini: kuburan. Dari perbincangan-perbincangan tentang sastra yang sangat sayup-sayup dalam masyarakat Toraja, saya bisa sedikit menangkap dan berani menyimpulkan bahwa sebagian besar orang Toraja menganggap sastra sebatas pada ucapan-ucapan To Minaa dan berbagai hal yang serupa dengan itu.
Dalam catatan sejarah, sastra adalah salah satu komponen terpenting. Orang dapat mengetahui mengenai kebudayaan Yunani yang menjadi fondasi peradaban Barat melalui karya-karya sastra, salah satunya melalui Homerus dalam The Iliad yang mengisahkan mengenai Perang Troya. Dari India, salah satu epos yang sangat dikagumi adalah kisah perang Baratayudha, perang saudara antara kelompok Pandawa dan Kurawa dalam Mahabbarata. Isi Mahabbarata sangat berpengaruh pada kebudayaan Jawa. Bahkan, seorang misionaris Belanda utusan Nederlandsch Bijbelgenootschap (Lembaga Alkitab Belanda) bernama Dr. B.F. Matthes pada masa kolonialisme telah memboyong salah satu maha-karya sastra yang berasal dari Sulawesi, I La Galigo. Sekarang tersimpan di Leiden, Negeri Belanda. Naskah I La Galigo adalah naskah yang sangat penting bagi sejarah Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan masa lalu. Singkatnya, sastra telah memberikan harta yang tak ternilai dalam perjalanan peradaban manusia, karena melalui karya-karya sastra orang dapat membaca ‘jejak’ masa lampau. Berhadapan dengan karya-karya sastra yang “wah..” seperti itu, kita mungkin akan merasa “kecil”. Tetapi, dari beberapa kawan saya yang dari latar-belakang sastra dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, ternyata sastra tidak hanya terkait dengan karya-karya “besar” saja. Berpuisi, menulis cerpen, menulis novel, dll, adalah dunia sastra, yang sebagian besar bisa dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja.
Kembali kepada Novel Landorundun. Saya tidak akan membicarakannya dengan metode-metode kritik sastra yang cakupannya begitu luas, yang seperti filsafat bagaikan sebuah 'rimba-raya' teori. Sementara saya hanyalah orang baru yang tidak memiliki 'kompas' di tangan di tengah rimba-raya kritik sastra tersebut. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah ini akan menjadi momentum kebangkitan sastra di Toraja, yang selalu berbangga sekaligus 'resah' dengan budayanya? Seberapa jauh sastra memiliki peluang untuk hidup di tengah-tengah masyarakat Toraja? Seberapa penting sastra untuk 'hidup' di Toraja? Dua pertanyaan awal akan terjawab oleh waktu, sementara pertanyaan ketiga adalah pertanyaan yang krusial yang mendasari pertanyaan pertama dan kedua.
Ya, seberapa penting sastra itu bagi orang Toraja? Ketika membaca Novel Landorundun, saya menemukan “cermin” masyarakat Toraja sekarang, yang tidak sepenuhnya 'tradisional' tetapi juga tidak sepenuhnya 'modern'. Ada sisi-sisi dimana ketika dicermati akan membuat identitas 'ketorajaan' yang tampak stabil menjadi goyah. Misalnya, dalam diri Kinaa Landorundun: apakah ketorajaan itu berdasarkan keturunan darah-daging atau budaya yang dihidupi? Walaupun Kinaa mewarisi darah Toraja dari ayahnya, tetapi ia lahir dan besar di luar Sulawesi. Ketika ia ke Toraja, ia adalah 'orang asing': wajah bule (dari ibu), tinggal di hotel, sangat minim pengetahuan tentang Toraja, dll. Atau Ayah Kinaa, yang tidak mau pulang-kampung karena 'sesuatu dan lain hal' yang telah terjadi ketika masih di kampung. Bukankah ini cerminan dari yang me(di)namakan diri 'orang Toraja', yang konon berjumlah sekitar 2.000.000 orang, dan hanya sekitar 600.000 yang berada di wilayah Toraja? Dengan kata lain, melalui novel, sang penulis sedang membicarakan tentang realitas sosial, bahkan kita bisa menemukan di beberapa bagian tertentu: kritik sosial!!!
Disadari atau tidak, masyarakat Toraja, khususnya yang berada di Toraja sedang berada dalam ritme budaya yang cukup cepat dan terus berubah. Orang tidak bisa lagi mengandalkan 'cara lama' dalam pusaran masyarakat yang begitu tidak menentu. Bukankah kita telah melihat robohnya 'cara lama' dalam ritual yang paling fenomenal dari Toraja yakni rambu solo’ dan semua upaya untuk mengembalikannya justru menghasilkan bentuk-bentuk baru? Bukankah banyak orang Toraja terperangah atas kehadiran 'predator' yang menjadi salah satu tanda goyahnya tatanan moralitas ortodoks? Lalu banyak orang 'megap-megap', hanya bisa mengelus dada dan mengatakan “o indo’ ku le...”.
Masyarakat Toraja sebagai subyek aktif kebudayaan berada dalam ketegangan-ketegangan yang telah, sedang dan akan terus menciptakan 'identitas-identitas' baru. Novel Landorundun telah membuka sebuah gerbang baru bagi kita.
Salama'....
NB: Ditulis pada tanggal 3 Januari 2013. Pernah dipublikasikan di Toraja Cyber News.
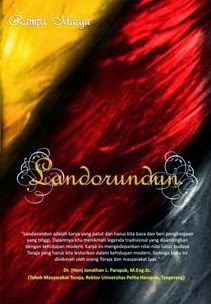
.jpg)











